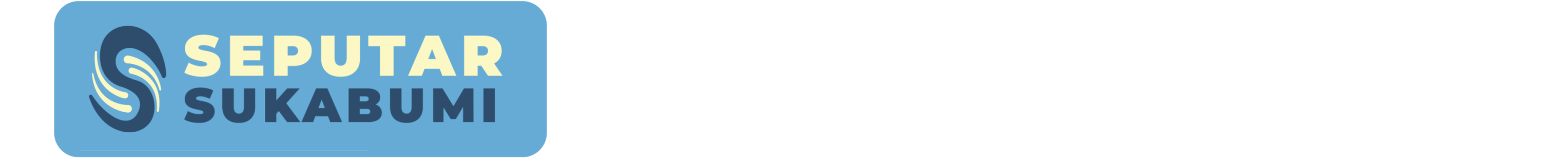SEPUTARSUKABUMI – Peringatan Serentahun Kasepuhan Gelaralam pada 3 Oktober 2025 menjadi momen penting bagi masyarakat adat di Sukabumi. Acara tersebut dirangkaikan dengan Riungan Gede Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) ke-12, yang dihadiri oleh para ‘olot’ (sesepuh) dan utusan kasepuhan dari empat kabupaten: Sukabumi, Bogor, Lebak, dan Pandegelang.
Di tengah kegiatan tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menyebut bahwa hadirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah kado terbaik bagi masyarakat adat. Perda ini disahkan bertepatan dengan peringatan Riungan Gede SABAKI dan Seren Tahun Gelaralam.
Menurut Bayu, eksistensi masyarakat adat di Sukabumi sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Mereka mewarisi amanat leluhur tentang pola hidup yang selaras dan harmonis dengan alam. “Dengan adanya perda tersebut, masyarakat adat sebagai subjek hukum telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi,” tuturnya, Minggu (5/10/2025).
Ia menjelaskan, setelah pengakuan hukum diperoleh, langkah selanjutnya adalah perjuangan untuk mendapatkan hak kepemilikan wilayah adat. Keberadaan perda ini menjadi syarat penting dalam pemenuhan persyaratan pengajuan wilayah adat.
Konsep Konservasi Tradisional: Cinyusu Rumaten dan Patanjala
Masyarakat kasepuhan di Sukabumi memiliki sistem pengetahuan tradisional yang mengatur tata guna lahan, seperti Gunung Kaian, Gawir Awian, hingga Dataran Sawahan. Di antara istilah-istilah tersebut, konsep ‘Cinyusu Rumaten’ menjadi simbol komitmen masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan sumber mata air.
Selain kasepuhan, terdapat juga komunitas masyarakat asal di luar wilayah hukum adat yang tetap memegang teguh nilai tradisi. Komunitas ini tersebar di kawasan sungai, seperti Sungai Cicatih, Sungai Cimandiri, Sungai Cipelang, dan Sungai Citarik.
Komunitas-komunitas ini memiliki entitas pengetahuan tradisional dalam menjaga kawasan sungai (pangauban). Dasar pengetahuan tersebut bersumber dari Naskah Amanat Galunggung, yang memuat ajaran Prabu Darmasiksa, Raja Pakuan abad ke-13. Naskah tersebut menyebutkan kalimat: “Kuna urang ala lwirna patanjala, Pata ngarana cai jala ngarana apya…” yang bermakna “Kita ikuti cara mengalirnya patanjala, pata artinya air dan jala artinya wilayah air.”
Dari naskah tersebut lahirlah sistem Pengetahuan Tradisional Patanjala, yakni metode penetapan wilayah atau zonasi berdasarkan daerah tangkapan air (gentong bumi). Patanjala membagi pola ruang menjadi kawasan larangan (pelestarian alam), tutupan (perlindungan), dan baladahan (pemanfaatan/budidaya).
Struktur ruang dalam Patanjala juga mengenal pembagian wilayah karamaan (hulu/spiritual), karesian (tengah/pusat pengetahuan), dan kaprabuan (hilir/pusat pemerintahan).
Raperda Patanjala sebagai Landasan Hukum Pelestarian
Pengetahuan tradisional yang dilestarikan masyarakat asal ini kini diformulasikan menjadi norma dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Kawasan Sumber Air (Patanjala).
Bayu Permana menjelaskan bahwa Raperda Patanjala memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai tradisi kasepuhan, khususnya konsep ‘Cinyusu Rumaten’. Ia berharap perda ini kelak dapat melengkapi Perda Masyarakat Hukum Adat dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemetaan wilayah adat serta mengembalikan fungsi kawasan.
“Semoga upaya-upaya ini sejalan dengan cita-cita dan amanat para leluhur, yaitu gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” tutupnya.